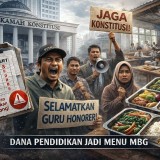TIMES MATARAM, MATARAM – Isu laporan dugaan ijazah palsu yang menyeret nama mantan Presiden Indonesia, Joko Widodo yang akrab disapa Jokowi semakin memanas. Beberapa waktu lalu dengan segala hormat guru saya Prof. Dr. Sofian Effendi menyampaikan pernyataan yang menyangsikan status Jokowi sebagai alumni UGM.
Pernyataan tersebut dibantah UGM yang menyebutkan bahwa ijazah atas nama Saudara Joko Widodo tetap pada pernyataan yang disampaikan dalam siaran pers 15 April 2025 di halaman website UGM.
Di siaran pers tersebut dijelaskan bahwa Joko Widodo adalah alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Yang bersangkutan telah melaksanakan seluruh proses studi yang dimulai sejak tahun 1980 dengan nomor mahasiswa 80/34416/KT/1681 dan lulus pada tanggal 5 November 1985.
Saya tidak ingin terjebak pada diskursus di atas. Sebagai analis kebijakan publik profesional, saya ingin menyampaikan bahwa bagi analis kebijakan publik, kasus ini dapat dibedah dari dua perspektif yakni analisa keabsahan dokumen dan analisa politik.
Perspektif pertama melihatnya dari sudut pandang hukum, berproses di wilayah yudikatif dan berakhir dengan putusan pengadilan. Sedangkan perspektif kedua melihatnya dari dinamika politik yang berproses di ruang narasi publik dan tidak memiliki akhir.
Artikel ini memilih menggunakan perspektif kedua dengan asumsi dasarnya bahwa dalam konteks politik saat ini, Indonesia cenderung polarisatif dan rentan dengan narasi-narasi kontroversial, tuduhan seperti ini tidak hanya berdimensi hukum atau akademis, tetapi juga memiliki dimensi politik yang cukup dalam.
Sebaiknya analisis kasus ini dilihat dalam konteks adanya tekanan politik terhadap pemerintah yang semakin tinggi, baik dari kelompok oposisi maupun dari elemen masyarakat sipil yang merasa tidak puas dengan kebijakan-kebijakan pemerintah.
Bersamaan dengan situasi tersebut, isu-isu yang bersifat personal, seperti riwayat pendidikan, latar belakang keluarga, atau rekam jejak karier digunakan sebagai amunisi politik yang dipandang efektif untuk menggoyahkan legitimasi seorang pemimpin.
Dengan meletakkan argumentasi ini maka semakin mudah mendudukkan tuduhan ijazah palsu bukan hanya sekadar pertanyaan tentang keabsahan dokumen, tetapi lebih jauh lagi menjadi alat untuk membangun persepsi negatif terhadap citra Jokowi sebagai presiden.
Oleh karena analisis ini menggunakan perspektif politik, maka ada tiga teori yang dipandang relevan yakni teori kekusaan, pengaruh, dan kekuatan. Dari sisi teori kekuasaan, kasus ini memberikan gambaran bagaimana kekuasaan tidak hanya berada di tangan penguasa formal, tetapi juga bisa diperebutkan melalui narasi, informasi, dan opini publik.
Dalam konteks ini kelompok oposisi atau aktor non-negara menggunakan isu-isu seperti yang bersifat moral personal untuk menantang dominasi penguasa yang sedang menjabat. Adapun dari perspektif teori pengaruh, kita dapat melihat bagaimana isu “ijazah palsu Jokowi” dimanfaatkan untuk membentuk agenda politik tertentu, baik melalui media sosial, pemberitaan media mainstream, maupun diskusi-diskusi di ruang publik.
Sedangkan dari perspektif teori kekuatan, kita bisa membaca isu “ijazah palsu Jokowi” sebagai pertarungan dominasi kekuatan politik untuk digunakan sebagai modal mendapatkan kekuasaan pada kontestasi pemilu di masa mendatang.
Teori Kekuasaan dan Dinamika Politik dalam Kasus Ijazah Palsu Jokowi
Dalam kerangka teori kekuasaan, khususnya seperti yang dikembangkan oleh Michel Foucault (1980) menyatakan bahwa kekuasaan tidak dimiliki oleh subjek tunggal, tetapi berada di mana-mana dalam jaringan relasi sosial. Selain itu Max Weber (1978) menyebutkan kekuasaan terbagi menjadi tiga jenis: tradisional, karismatik, dan legal-rasional.
Dengan mencermati pemikiran kedua tokph di atas, nampak bahwa kekuasaan tidak hanya dimiliki oleh lembaga formal seperti negara, tetapi juga tersebar dalam berbagai relasi sosial, institusi, kelas, kelompok, partai politik dan narasi.
Berpijak dari teori ini maka kasus laporan “ijazah palsu Jokowi”, menjelaskan pada kita tentang bagaimana kekuasaan digunakan untuk menantang legitimasi seorang pemimpin melalui mekanisme simbolik dan narasi politik. Tuduhan terhadap Jokowi bukan hanya bertujuan untuk mengoreksi kesalahan administratif, tetapi juga untuk mengurangi legitimasi politiknya sebagai presiden.
Misalnya ketika Foucault (1978) menyebut bahwa kekuasaan tidak hanya represif, tetapi juga produktif dan bekerja melalui berbagai media, maka ini artinya kekuasaan tidak hanya digunakan untuk menindas, tetapi juga untuk menciptakan realitas tertentu.
Dalam kasus ini, tuduhan ijazah palsu mencoba menciptakan sebuah realitas alternatif di mana Jokowi dianggap tidak layak menjadi presiden karena ketidakabsahan status akademisnya. Narasi ini kemudian disebarkan melalui media sosial, forum diskusi, dan pemberitaan media sehingga membentuk opini publik yang bisa memengaruhi persepsi terhadap pemerintah.
Selanjutnya dengan menggunakan pemikiran Maax Weber (1978) yang membagi legitimasi kekuasaan menjadi tiga jenis: tradisional, karismatik, dan legal-rasional. Maka dalam menjelaskan konteks Indonesia, Jokowi memiliki legitimasi karismatik yang kuat karena latar belakangnya sebagai mantan pedagang mebel yang naik menjadi wali kota, gubernur, dan akhirnya presiden.
Namun, ketika ada upaya untuk mempertanyakan validitas ijazahnya, hal ini secara tidak langsung mencoba merusak legitimasi karismatik tersebut dengan mengubah narasi publik bahwa Jokowi adalah orang biasa yang sukses karena integritasnya. Jika ia dituduh memperoleh gelar akademis secara tidak sah, maka citra karismatiknya akan tercoreng, dan legitimasinya sebagai pemimpin bisa terancam.
Penjelasan lainnya bisa diperoleh melalui teori Hegemoni yang diprakarsai Gramsci (2005) yang pada pokonya menjelaskan bagaimana kekuasaan bekerja melalui budaya, ideologi, dan konsensus, bukan hanya melalui negara dan kekerasan.
Ia ingin mengatakan bahwa elite mendominasi ideologi masyarakat tanpa paksaan fisik dan bisa bekerja melakukan hegemoni melalui kontrol atas narasi, media, dan institusi budaya.
Dalam kasus ini, tuduhan “ijazah palsu Jokowi” bisa dilihat sebagai upaya untuk mengganggu hegemoni pemerintah dengan menciptakan narasi alternatif yang menantang kebenaran resmi, tanpa sedikitpun melakukan tindakan kekerasan.
Kelompok oposisi atau aktor yang tidak setuju dengan pemerintah mencoba menggeser hegemoni dengan membangun argumen bahwa Jokowi tidak memiliki kapabilitas yang seharusnya dimiliki oleh seorang presiden.
Bahkan yan terbaru teori kekuasaan dari Steven Lukes (2005) yang menjelaskan adanya tiga dimensi kekuasaan yakni visible, hidden, dan invisible. Dimensi pertama, visible power, tampak dalam bentuk laporan hukum resmi yang diajukan oleh pelapor.
Dimensi kedua, hidden power, terletak pada kemampuan aktor-aktor politik untuk mengendalikan agenda pembicaraan agar isu ini tetap hidup di ruang publik.
Sementara itu, dimensi ketiga, invisible power, berkaitan dengan pengaruh tersembunyi yang membentuk preferensi masyarakat, sehingga mereka mulai meragukan keabsahan kepemimpinan Jokowi bahkan tanpa sadar.
Dengan demikian, kasus laporan “ijazah palsu Jokowi” bukan hanya soal benar atau salahnya dokumen akademis, tetapi juga refleksi dari pertarungan kekuasaan di tingkat ideologis dan naratif.
Melalui lensa teori kekuasaan, kita dapat melihat bahwa isu ini menjadi arena bagi kelompok-kelompok politik untuk merebut atau mempertahankan dominasi ideologis mereka dalam sistem politik Indonesia.
Pengaruh Media dan Opini Publik dalam Membentuk Narasi Politik
Media massa, baik konvensional maupun digital, memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk narasi politik, termasuk dalam kasus l”ijazah palsu Jokowi”. Dalam era digital seperti saat ini, informasi menyebar dengan sangat cepat, dan media sosial menjadi saluran utama penyebaran narasi politik yang sering kali bersifat provokatif dan tendensius.
Dalam konteks ini, media tidak hanya bertindak sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai aktor politik yang ikut membentuk persepsi publik terhadap seorang pemimpin.
Dalam teori pengaruh, Robert Dahl dan Anthony Downs (1961) dalam teori pluralisme, menyatakan bahwa kekuasaan politik tidak terkonsentrasi dalam satu tangan, tetapi terbagi di antara berbagai kelompok kepentingan dan aktor politik. Oleh karenanya mereka menggarisbawahi pentingnya opini publik dalam menentukan arah kebijakan politik.
Opini publik tidak selalu muncul secara spontan, tetapi sering kali dibentuk melalui framing dan agenda-setting oleh media. Dalam kasus laporan ijazah palsu Jokowi, media menjadi alat yang digunakan oleh kelompok tertentu untuk membentuk narasi yang bisa merusak reputasi presiden.
Framing ini dilakukan dengan memilih angle tertentu dalam pemberitaan, misalnya dengan fokus pada aspek kontroversial tanpa memberikan ruang yang proporsional untuk klarifikasi dari pihak Jokowi atau institusi pendidikan terkait.
Salah satu contoh paling jelas dari penggunaan media sebagai alat pembentuk narasi adalah fenomena viral di media sosial. Ketika laporan tersebut pertama kali muncul, berbagai unggahan di Twitter, Facebook, dan YouTube memuat klaim-klaim yang belum tentu diverifikasi secara faktual.
Video editan, screenshot palsu, atau kutipan yang diambil di luar konteks sering kali digunakan untuk memperkuat narasi bahwa Jokowi memiliki riwayat akademik yang tidak benar. Hal ini menunjukkan bagaimana media sosial dapat menjadi arena pertarungan informasi di mana fakta dan opini sulit dibedakan.
Selanjutnya ada teori spiral of silence dari Elisabeth Noelle-Neumann (1974) menjelaskan bahwa opini publik cenderung didominasi oleh kelompok mayoritas yang percaya diri menyuarakan pandangannya, sementara kelompok minoritas cenderung diam karena takut dikucilkan.
Dalam konteks kasus ini, ketika tuduhan ijazah palsu terus-menerus diangkat di media dan platform digital, kelompok yang mendukung Jokowi mungkin merasa terpojok dan enggan menyuarakan dukungan mereka, terutama jika mereka berada di lingkungan yang cenderung kritis terhadap pemerintah. Akibatnya, persepsi publik bisa terdistorsi, seolah-olah mayoritas masyarakat percaya pada tuduhan tersebut padahal belum tentu demikian.
Pengaruh media juga terlihat dari cara pemerintah dan partai politik pendukung Jokowi merespons isu ini. Alih-alih mengabaikan atau menyangkal secara langsung, beberapa pihak justru memilih untuk menghindari komentar yang bisa memperkeruh suasana.
Strategi ini mungkin bertujuan untuk menghindari eskalasi politik lebih lanjut, tetapi di sisi lain, sikap diam tersebut bisa diinterpretasikan sebagai bentuk kelemahan atau pengakuan atas kebenaran tuduhan tersebut. Ini menunjukkan betapa besar pengaruh media dalam menentukan respons politik dari pihak-pihak yang terlibat.
Sejalan dengan pandangan teori di atas, teori mediatization dari Hartmut Wessler dan Daniel C. Hallin (2008) menyebutkan bahwa politik modern semakin bergantung pada logika media, di mana keputusan politik sering kali dibuat dengan mempertimbangkan bagaimana pemberitaan akan menampilkan narasi tersebut. Oleh karenanya politisi semakin menyesuaikan cara kerja mereka dengan logika media, seperti kebutuhan akan visualisasi, dramatisasi, dan narasi yang menarik.
Dalam kasus ini, kemungkinan besar tim komunikasi presiden dan partai pendukung melakukan analisis media sebelum merespons tuduhan tersebut. Keputusan untuk tidak bereaksi secara emosional dan lebih memilih menyerahkan proses hukum kepada aparat berwenang mungkin merupakan strategi untuk menghindari framing negatif yang lebih luas.
Secara keseluruhan, media memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk narasi politik seputar laporan ijazah palsu Jokowi. Dari framing pemberitaan hingga interaksi di media sosial, semua ini memengaruhi persepsi publik dan dinamika politik di Indonesia.
Dengan menggunakan teori pengaruh, kita dapat memahami bahwa media bukan hanya cerminan realitas, tetapi juga aktor yang aktif menciptakan realitas tersebut.
Kekuatan Formal dan Informal dalam Reaksi Politik
Dalam konteks kasus laporan “ijazah palsu Jokowi”, reaksi politik yang muncul dari berbagai pihak tidak hanya didasarkan pada fakta hukum atau akademis, tetapi juga pada kekuatan formal dan informal yang saling berinteraksi.
Kekuatan formal seperti lembaga hukum, partai politik, dan birokrasi negara memiliki peran yang jelas dalam menangani laporan tersebut, sementara kekuatan informal seperti kelompok masyarakat sipil, tokoh agama, dan influencer media sosial turut membentuk dinamika respons politik yang lebih luas.
Lembaga hukum, khususnya Polri, menjadi kekuatan formal pertama yang terlibat dalam menindaklanjuti laporan tersebut. Proses hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian menjadi tolok ukur apakah klaim tersebut memiliki dasar yang kuat atau hanya sekadar narasi politik.
Dalam konteks ini, kekuatan formal seperti Polri tidak hanya bertugas untuk menegakkan hukum, tetapi juga menjadi aktor yang menentukan apakah laporan tersebut akan berkembang menjadi kasus hukum atau tidak.
Apabila hasil penyelidikan menunjukkan bahwa klaim tersebut tidak terbukti, maka legitimasi Jokowi sebagai presiden akan tetap terjaga. Sebaliknya, jika ada indikasi pelanggaran, maka hal ini bisa menjadi pintu masuk bagi kelompok oposisi untuk memperkuat narasi anti-pemerintah.
Partai politik pendukung Jokowi juga merupakan kekuatan formal yang berperan dalam merespons laporan tersebut. Partai-partai seperti PDIP, Golkar, NasDem, dan PPP memiliki kapasitas untuk mengorganisir dukungan politik, menggerakkan mesin partai, dan memobilisasi massa untuk membela presiden.
Dalam konteks ini, partai-partai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai alat kampanye politik, tetapi juga sebagai benteng pertahanan ideologis yang bertujuan untuk menjaga stabilitas koalisi pemerintah.
Reaksi politik yang terkoordinasi dari partai pendukung Jokowi bisa membantu mengurangi dampak negatif dari tuduhan tersebut, baik melalui pernyataan resmi, aksi solidaritas, maupun pengerahan massa untuk mendukung pemerintah.
Di sisi lain, kekuatan informal seperti kelompok masyarakat sipil, aktivis, dan tokoh agama juga memiliki pengaruh yang tidak bisa diabaikan. Kelompok masyarakat sipil sering kali menjadi penyeimbang kekuasaan dengan memberikan kritik konstruktif atau dukungan terhadap pemerintah.
Dalam kasus ini, ada kelompok yang mendukung investigasi independen terhadap klaim tersebut, sementara yang lain mengecamnya sebagai upaya black campaign yang tidak produktif. Tokoh agama juga memiliki peran penting dalam membentuk opini publik, terutama dalam konteks masyarakat Indonesia yang religius.
Dukungan dari ulama atau tokoh agama terkemuka bisa membantu memperkuat legitimasi Jokowi, terutama di kalangan pemilih Muslim yang menjadi basis utama dukungan politiknya.
Selain itu, influencer media sosial dan selebritas juga menjadi kekuatan informal yang ikut membentuk narasi politik seputar kasus ini. Di era digital, opini dari individu-individu dengan jumlah pengikut besar bisa lebih cepat menyebar daripada pernyataan resmi dari lembaga formal.
Influencer ini bisa memperkuat narasi pro-pemerintah dengan memberikan dukungan terbuka kepada Jokowi atau sebaliknya, memperluas klaim tersebut dengan membagikan informasi yang belum diverifikasi. Peran mereka dalam membentuk opini publik tidak bisa diremehkan, karena jangkauan dan pengaruhnya yang sering kali melebihi institusi formal.
Melalui interaksi antara kekuatan formal dan informal ini, dinamika politik seputar laporan ijazah palsu Jokowi menjadi lebih kompleks. Bukan hanya soal benar atau salahnya tuduhan, tetapi juga bagaimana berbagai aktor politik menggunakan kekuatan mereka untuk mempertahankan atau menggoyahkan legitimasi seorang presiden.
Dengan memahami peran masing-masing kekuatan ini, kita bisa melihat bahwa kasus ini bukan hanya soal hukum atau akademis, tetapi juga arena pertarungan politik yang melibatkan berbagai aktor dengan kepentingan berbeda.
Kasus laporan “ijazah palsu Jokowi” membuktikan bahwa politik di Indonesia tidak hanya berlangsung dalam ranah formal seperti lembaga negara dan partai politik, tetapi juga dalam narasi, media, dan persepsi publik.
Dari analisis teori kekuasaan, pengaruh, dan kekuatan, terlihat bahwa isu ini menjadi ajang pertarungan ideologis di mana berbagai aktor politik berusaha membangun legitimasi atau sebaliknya, merusak reputasi seorang pemimpin.
Tuduhan terhadap Jokowi bukan hanya soal keabsahan dokumen akademis, tetapi juga refleksi dari dinamika kekuasaan yang lebih luas, di mana narasi bisa menjadi senjata politik yang ampuh.
Implikasi dari kasus ini terhadap tatanan demokrasi Indonesia cukup signifikan. Di satu sisi, masyarakat semakin kritis dan aktif dalam mengawal transparansi politik, namun di sisi lain, polarisasi yang semakin tajam bisa mengganggu stabilitas politik nasional.
Selain itu, media sosial yang seharusnya menjadi alat penguat demokrasi justru acapkali menjadi sarana penyebaran hoaks dan narasi tendensius yang memicu konflik horizontal.
***
*) Oleh : Dr. Agus, M.Si., Peneliti PuSDeK UIN Mataram.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggungjawab penulis, tidak menjadi bagian tanggungjawab redaksi timesindonesia.co.id
*) Kopi TIMES atau rubik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
*) Naskah dikirim ke alamat e-mail: [email protected]
*) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim.
| Pewarta | : Hainor Rahman |
| Editor | : Hainorrahman |